Bima Satria Putra
Ekologi Sosial: Sebuah Pengantar
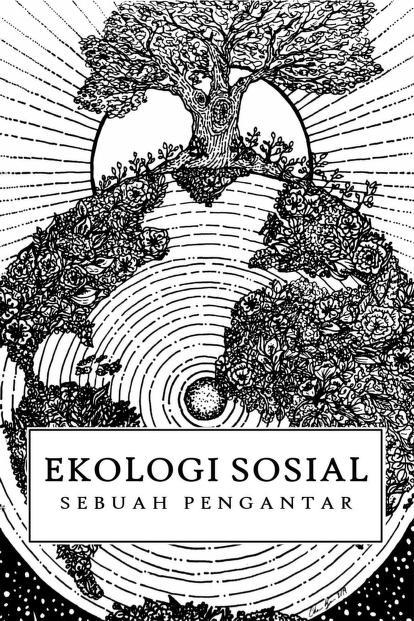
Dulu saya sempat mengutuk manusia karena sifat parasitik yang merusak inangnya, bumi. Saya menganggap bumi sebagai insan yang hidup dan kita sebagai virus. Virus membunuh bumi, dan ketika inangnya mati, virus turut mati. Itu sebabnya dulu saya berpendapat bahwa eksistensi kita sebagai spesies itu tidak hanya salah, tetapi juga berbahaya. Kepunahan Homo sapiens akan menjadi jalan keluar untuk membuat bumi tetap “selamat”. Ide semacam ini direproduksi dalam banyak produk budaya populer, khususnya film, dan mung- kin anda salah satu yang berpikir demikian. Saya berubah pikiran setelah menerjemahkan esai-esai Murray Bookchin.
Bookchin tidak melihat manusia sebagai sesuatu yang asing dari alam. Memang, Bookchin menekankan bahwa ada dua dunia, yaitu dunia alam dan dunia manusia. Tetapi ia melihat keduanya sebagai suatu jalinan dan terpaut. Manusia ada karena sejauh ini alam memang mengizinkan kita dalam tahap evolusinya: kita sendiri adalah alam. Meski kita sering membedakan produk material manusia seperti beton, listrik dan rekayasa lain sebagai tidak alamiah, Bookchin berpenda- pat bahwa itu semua adalah sama alamiahnya dengan berang- berang yang membuat bendungan dari ranting pohon di su- ngai atau seperti tupai menggali lubang di tanah. Dalam esai What is Social Ecology? Bookchin berpendapat:
“Manusia menjadi bagian dari rangkaian alami (natural continuum), tidak kurang seperti nenek moyang primata dan mamalia mereka secara umum... Tentu saja, pemikir lingkungan yang hingga derajat tertentu meromantisir alam non-manusia sebagai yang liar dan melihatnya secara otentik lebih “alami” ketimbang hasil karya manusia, telah membekukan sifat non- manusia sebagai domain terbatas dimana inovasi manusia, pandangan ke masa depan, dan kreativitas tidak memiliki tempat dan tidak menawarkan kemungkinan apapun. Yang betul adalah bahwa manusia tidak hanya milik alam, mereka adalah produk yang panjang, proses evolusioner alami.”
Jika anda membaca Sapiens karya Yuval Noah Harari, ia menyebut tahap perkembangan untuk membedakan spesies manusia dari yang non-manusia sebagai “revolusi kognitif”. Bookchin punya gagasan serupa. Ia menyebutnya sebagai “pemikiran konseptual”. Ini dapat dijelaskan sebagai: “kekuatan untuk membentuk komunitas yang sangat dilembagakan yang disebut masyarakat... manusia mampu melakukan pengembangan evolusioner mereka sendiri, sebagaimana ia telah memungkinkan untuk berakar di alam.” Pandangan Bookchin punya banyak konsekuensi. Terutama Ekologi Sosial meminta kita lebih mawas diri terhadap eksistensi kita sebagai spesies “alamiah”. Sederhananya begitu. Kedua, Ekologi Sosial memberikan penekanan bahwa kita punya kapasitas untuk menyetir perkembangan masyarakat kita sendiri. Itu sebabnya Ekologi Sosial memusatkan dirinya pada pembahasan meng- enai pertumbuhan hirarki dan gagasan untuk mendominasi alam, serta bagaimana kita dapat membaliknya.
Peter Kropotkin dalam Mutual Aid telah mengeksplorasi bentuk solidaritas, cinta kasih dan saling membantu, sementara Marcel Mauss dalam karyanya The Gift, telah berkontribusi untuk mengingatkan kita bahwa saling memberi (dikenal sebagai gift economy) adalah salah satu fondasi awal masyarakat. Keduanya menunjukkan bahwa yang alternatif itu sebenarnya bukanlah kerjasama, tetapi persaingan: bukan egalitarianisme tetapi hierarki. Saya khawatir bahwa panda- ngan liberal atau individualis akan keliru memahami maksud saya karena perdebatan harfiah dari suatu teks (tapi biarlah begitu). Yang jelas, sebagian besar sejarah manusia sebenar- nya justru ditandai oleh bentuk yang pertama, dan kita menu- rut Bookchin, telah “menyimpang” menuju yang terakhir. Yang terakhir inilah yang menyeret kita pada kehancuran besar-besaran. Beruntungnya, pemikiran konseptual kita itu pula yang memungkinkan kita untuk menyetir ke arah mana diri kita dan masyarakat hendak menuju.
Jelas ini akan menabrak asumsi dasar antropologi evolusioner yang beranggapan bahwa negara adalah tujuan akhir dari tahap perkembangan masyarakat manusia. Sebaliknya bagi Bookchin, kita punya banyak kemungkinan. Karena kita pernah menerapkan prinsip-prinsip yang berbeda dari masyarakat saat ini, maka bukan hal mustahil kita mampu mempertahankan dan mengembalikannya. Hal ini penting bukan saja karena hal itu baik dan memungkinan, tetapi itu diperlukan. Ini salah satu alasan mengapa Bookchin meninggalkan politik Marxisme, tetapi menciptakan perpaduan yang menarik dari- nya dengan anarkisme. Tapi, keyakinan akan kapasitas man- usia untuk membentuk masyarakatnya yang bakal jadi fon- dasi awal dan mendasar dari Ekologi Sosial.
Biasanya politik anarkisme disepelekan karena meromantisir kehidupan masa lalu yang bersahaja dan dianggap tidak realistis. Tetapi Bookchin berpendapat bahwa situasi hari ini menunjukkan bahwa pilihan yang tersedia adalah perubahan sosial atau kiamat. Bookchin menelusuri konteks historis dari perkembangan gagasan anarkis modern (meski hanya di Eropa). Ia merujuk pada gerakan anarkisme awal yang fokus pada pembentukan komune pedesaan pada abad pertengahan, karena kekuatan revolusioner saat itu adalah petani dari dunia feodal agraris. Anarkisme ala Proudhon berkembang saat para pengrajin urban terancam oleh revolusi industri. Ketika mesin-mesin dan asap pabrik menjadi bentuk mode produksi yang baru, dan kelas buruh industrial tercipta, maka lahirlah anarko-sindikalisme (bersamaan dengan marxisme). Situasinya saat ini berbeda: “Masalah baru muncul di mana pendekatan ekologis menawarkan arena diskusi yang lebih penting daripada pendekatan sindikalis yang lebih tua.”
Bookchin tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ide-ide lama tidak relevan (situasinya berbeda-beda tergantung pada wilayah). Sindikalisme mungkin diperlukan dalam pengorganisiran di kawasan industri, atau karena pada masa Bookchin teori-teori anarko-indigenisme belum mapan, bisa dibilang bahwa yang satu ini justru relevan bagi masyarakat adat. Maksud Bookchin dari arena diskusi yang lebih penting adalah degradasi lingkungan dan krisis iklim. Ide-ide eko- anarkisme dapat dilacak ke zaman yang lebih lama, mulai dari hak hewan, vegetarianisme, komunitas kecil yang hijau, bahkan ketelanjangan. Tetapi situasi hari ini bagi Bookchin begitu mendesak sehingga eko-anarkisme (yang sebenarnya juga terdiri dari tradisi yang begitu beragam) harus maju ke depan. Saya akan ringkas situasi hari ini, di sini, supaya lebih relevan.
Ketika Bookchin mulai memusatkan perhatian pada masalah ekologi, dunia sedang memulai kehancurannya (nuklir, megapolitan, polusi batubara, pertanian monokultur). Ia jadi radikal kiri pertama yang menekankan krisis lingkungan dan iklim dalam bukunya, Our Synthetic Environment (1962). “Rangkaian peracunan yang tak ada habisnya, menyerang udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan hampir se- mua hidangan di meja makan malam,” tulis Bookchin dalam esai Ecology and Revolutionary Thought pada 1964. Pada 2021 situasinya jelas lebih parah.
Penelitian menunjukkan bahwa plastik hasil konsumsi kita yang berujung di laut itu terurai menjadi mikroplastik yang tak kasat mata, masuk ke dalam ikan-ikan dan membaur bersama garam yang kita konsumsi. Iklim jelas berubah secara alami dalam jangka panjang (ini berurusan dengan orbit atau rotasi bumi), tapi dampak aktivitas industrial telah mengarahkan kita pada perubahan iklim yang merusak bentuk keanekaragaman hayati yang ada saat ini dan mengubah banyak unsur hara kita menjadi pasir dan mineral sederhana yang tidak mampu menopang bentuk kehidupan yang kompleks (gurunisasi benar-benar dapat membuat bumi jadi mirip mars). Di Indonesia, hutan hujan tropis kita dihancurkan oleh pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit yang diawali dengan penebangan, pembakaran lahan, lalu kabut asap. Polusi PLTU batubara mengerikan, tetapi asap kendaraan bermotor saja sudah sangat merusak udara perkotaan. Kota- kota tumbuh semakin besar dan menggantungkan pangannya pada daerah-daerah pertanian yang terus dipecut untuk memproduksi secara cepat dan besar. Model pertanian dan logistik pangan kita benar-benar tidak ramah lingkungan. Ini diperparah dengan virus baru yang bermutasi dan penyakit dari gaya hidup modern, industrialisasi peternakan dan kehancuran hutan. Pada skala global, pola kehancuran itu serupa.
Menghadapi hal tersebut, Ekologi Sosial memberikan tawaran yang Bookchin klaim lebih rasional ketimbang kerabat eko-anarkis mereka (Ekologi Dalam dan anarko-primitifisme). Anarko-primitifisme diwakili pemikir John Zerzan, Ted Kaczynski dan Kevin Tucker, yang pada 1990'an, menjadi lawan debat Bookchin yang sengit. Mereka punya pandangan yang beragam, tetapi mengusulkan penghancuran total atas peradaban, khususnya kritik keras terhadap teknologi dan industri, yang umumnya sepakat dengan pengurangan populasi penduduk (bukan genosida!) Mereka cenderung simpatik pada masyarakat pemburu-peramu nomaden egaliter. Intinya, penyederhanaan kembali kehidupan peradaban berskala kecil.
Sebaliknya, Bookchin pada masanya mewakili sejenis optimisme ekstrim untuk menyelamatkan peradaban. Di saat orang banyak jijik terhadap berbagai pencapaian dan perkembangan teknologi, Bookchin justru berpendapat bahwa teknologi kecuali nuklir, pada dasarnya tidak merusak (meski begitu, ia mengakui bahwa “teknologi dapat memperbesar masalah atau bahkan mempercepat pengaruhnya”). Di saat orang-orang menyatakan bahwa populasi adalah penyebab masalah ekologis, Bookchin justru menolaknya dan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kerusakan lingkungan telah terjadi dalam masyarakat dengan populasi rendah. Di saat banyak yang menyatakan bahwa kita terlalu banyak mengkonsumsi, Bookchin membenarkan sekaligus menolaknya, karena gaya hidup itu sendiri adalah bentukan pasar. Kerusakah hutan Kalimantan demi kelapa sawit bukan didorong oleh permintaan pasar atas minyak goreng, tetapi karena keberagaman pangan kita semua hilang oleh gaya hidup instan yang dipromosikan pasar dan diperparah jam kerja yang mematikan. Pangan lalapan sayur segar, asinan, pengasapan, manisan, fermentasi, rebus, bakar, terganti oleh peningkatan makanan gorengan berkolestrol yang cenderung baru tapi meningkat (kita dulu pakai lemak hewani atau minyak kelapa dalam jumlah terbatas). Ini bukan salah konsumen, tapi pengondisian pasar.
Memusatkan perhatian pada masalah populasi, teknologi dan konsumerisme, menurut Bookchin bakal “cenderung memperhatikan gejala penyakit sosial yang suram ketimbang pada penyakitnya itu sendiri” serta “mendistorsi dan memprivatisasi masalahnya.” Menyoroti gejala ini berarti menekankan bahwa kita semua bertanggungjawab sama besarnya atas kerusakan eko-sistem dan berujung pada gerakan ekologi yang sekedar daur ulang sampah, mengurangi kelahiran bayi, bersepeda, hemat air dan listrik, membuang sampah pada tempat,nya membeli produk yang lebih ramah lingkungan, serta usulan-usulan lain yang sifatnya harian dalam hidup kita. Inilah yang Bookchin maksud dengan “privatisasi krisis lingkungan” (privatization of the environmental crisis). “Jika solusi utama terhadap masalah lingkungan adalah “hidup sederhana dan daur ulang yang militan, krisis pasti akan berlanjut dan meningkat,” tulisnya. Di saat bersamaan, “dunia anti-ekologi ini tidak akan disembuhkan oleh tindakan kenegaraan atau merubah bagian dari suatu undang-undang sedikit demi sedikit. Ini adalah sebuah dunia yang sangat membutuhkan perubahan struktural yang meluas
Ekologi Sosial menekankan bahwa dominasi terhadap alam berakar dari dominasi manusia atas manusia. Lalu apa pangkal masalah sosial kita? Kapitalisme dan hukum pertumbuhan ekonominya: tumbuh atau mati. Itu berarti penyebab dan dampak kerusakan ekologi tidak merata antara kaya dan miskin, kulit hitam atau putih, laki-laki atau perempuan, yang homoseksual dan heteroseksual, dan sebagainya. Kekeliruan kita dalam memandang sumber masalah ekologis akan menyeret, misal, orang miskin kota yang dianggap sama merusaknya karena ia mengendarai kendaraan bahan bakar minyak atau karena punya sembilan anak atau karena membeli deterjen atau orang miskin di kampung yang berburu hewan langka karena jepitan ekonomi.
Di saat bersamaan, Bookchin juga men-olak bahwa ini sekedar masalah moral para pengusaha yang terlalu serakah. Katakanlah ada seorang pengusaha yang berwawasan ekologis. Ia pasti akan terpojok dalam kelangsungan hidup di pasar karena hubungan kompetitif dengan pesaingnya. Ia berada dalam kerugian fatal dengan pesaingnya yang tidak punya kepedulian ekologis, yang memproduksi dengan biaya yang lebih murah walau merusak lingkungan, tetapi meraup keuntungan yang lebih tinggi untuk ekspansi modal lebih lanjut. Bisa jadi pesaing atau pengusaha yang tidak punya wawasan ekologis itu memang serakah atau jahat, tapi Bookchin menyatakan kalau “kapitalisme modern secara struktural telah bersifat amoral dan karenanya tidak terpengaruh oleh tuntutan moral.”
Produk ramah lingkungan itu lebih mahal (bandingkan harga mobil listrik dengan motor roda dua, atau panel surya ketimbang menghubungi PLN). Ini mencegah perubahan besar-besaran karena ketidakmampuan finansial masyarakat, dan ini justru mengalihkan tanggungjawab kerusakan bumi seolah-olah ada di pundak konsumen. Inilah tujuan utama kapitalisme hijau. Bisa jadi, mobil listrik dan panel surya lebih murah setelah cadangan minyak bumi dan batubara menipis. Tapi kebanyakan korporasi raksasa melabeli dirinya ramah lingkungan bukan karena punya itikad untuk perbaikan ekosistem, melainkan karena melihat perkembangan potensi pasar yang dinamis. Bahkan ada khayalan bahwa manusia mungkin perlu pindah ke planet lain (secara komersial) jika bumi menjadi tidak toleran lagi bagi manusia. Jelas, kapasitas yang tersedia untuk mengangkut mungkin hanya ada bagi orang-orang kaya (mirip seperti film 2012). “Lebih mudah membayangkan kehancuran bumi ketimbang kehancuran kapitalisme,” tulis Frederic Jameson. Padahal, kapitalisme lah yang menghancurkan bumi.
Karena Bookchin mengusulkan perubahan struktural ketimbang moral, ia juga jadi yang pertama dalam menyerang Spiritualisme dalam gerakan Ekologi Dalam yang menyembah dewa-dewi Bumi, atau misalnya, gerakan memeluk pohon. Hari ini, salah satu yang paling bersemangat dengan wacana macam itu adalah eko-feminisme. Bookchin juga menyatakan bahwa sebenarnya Ekologi Sosial menekankan perubahan spiritual. Hanya saja, perubahan itu bersifat naturalistik, bukan supernatural atau panteistik. Bookchin menyebutnya sebagai “etika saling melengkapi” (ethics of complementary): “manusia akan melengkapi makhluk non-manusia dengan kemampuan mereka sendiri untuk menghasilkan karya yang lebih kaya, kreatif, dan keseluruhan perkembangannya bukan sebagai spesies yang “dominan, tetapi sebagai pendukung.” Itu artinya, mengakui bahwa spesies manusia punya kapasitas yang tidak dimiliki oleh makhluk non-manusia lain:
“Dari sudut pandang evolusioner, manusia telah di- bentuk untuk secara aktif, sadar, dan purposif, dapat campur tangan ke dalam alam pertama dengan efekti- fitas yang tak tertandingi dan mengubahnya ke dalam skala planet. Merendahkan kapasitas ini berarti men- 11 yangkal dorongan evolusi alam terhadap kompleksitas dan subjektivitas organik itu sendiri -potensi alam pertama untuk mengaktualisasikan dirinya ke dalam intelektualitas yang sadar diri.”
Bookchin mengutuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan yang diukur berdasarkan standarnya negara dan modal. Coba lihat, tunawisma menjadikan koran yang judul utamanya adalah “Pertumbuhan Ekonomi Meroket!” dan menjadikannya sebagai alas tidur. Di Indonesia, pemerintah lazim menyebutnya sebagai “pembangunan”, yang paradigmanya merujuk pada ketentuan Bank Dunia dan arahannya dipegang para penguasa dan pengusaha lokal (dan global) yang diuntungkan dari tatanan dominasi dan eksploitasi hari ini. Bookchin menyerukan “batasan pertumbuhan”. Gerakan ekologi yang mencoba menyuarakan ini sebagai langkah awal untuk menyadarkan publik mengenai masalah lingkungan pasti bakal dicap sebagai “gerakan anti-pembangunan”. Tetapi jika “pembangunan” itu artinya para elit jadi yang paling banyak dalam mendapatkan keuntungan dari ekonomi yang terindustrialisasi, tampaknya kita memang harus anti-pembangunan. Jika kemajuan negara diukur dari berapa banyak bangunan beton yang megah (dimana itu tidak bermanfaat bagi kita), kita harus menghentikan kemajuan itu. Narasinya, seperti Bookchin tekankan dalam munisipalisme libertarian, pemisahan antara masyarakat dengan negara, yang merupakan dua hal berbeda dan sebenarnya saling bertentangan sejak awal. Kemajuan negara belum tentu menjadi kemajuan bagi masyarakat.
Tuntutannya harus dikembalikan ke awal: pembangunan itu mengorbankan kerusakan ekosistem, kehancuran makhluk manusia dan non-manusia. Jadi ini bukan karena kita tidak mendapatkan jatah dari proses penghancuran itu. Batasan ini sangat relevan dalam banyak hal. Pegunungan karst (yang jadi andalan aliran air bawah tanah) ditambang demi bahan baku semen, padahal produksi semen kita surplus dan menumpuk di gudang. Perkebunan kelapa sawit kita diperluas meski hasil panennya buruk (korporasi mengutamakan perluasan lahan ketimbang intensifikasi produksi). Batubara juga terus ditambang dan PLTU batubara baru dibangun, meski cadangan yang terpendam di bawah tanah secara nasi- onal sangat sedikit. Ini beresiko menciptakan ketergantungan untuk impor batubara satu dekade yang akan datang, yang membuat pemerintah menjadi lebih rentan didikte oleh lembaga donor internasional dan korporasi asing dibelakangnya. Batubara yang dibakar di PLTU lebih banyak ketimbang jumlah konsumsi listrik masyarakat (gerakan mematikan listrik selama satu jam atau satu hari menunjukkan betapa tidak efektifnya gerakan ekologi yang mengkompensasi kapitalisme hijau ini). Semua proses ini berlangsung dengan mengorbankan hutan, yang beresiko menciptakan penyakit baru dari mutasi virus-virus yang dulu hanya menjangkiti hewan liar dan sebaliknya.
Ketika gerakan buruh di Eropa semakin kuat dan banyak yang berhasil mendapatkan “kesejahteraan”, para kapitalis memindahkan pabrik-pabrik mereka ke negara-negara Dunia Ketiga yang tidak terindustrialisasi. Dengan alasan mencipta- kan lapangan pekerjaan (yang berarti proletarisasi lebih lanjut atas penduduk Indonesia), birokrasi harus dipangkas dan investasi dipermudah. Di saat bersamaan, upah buruh mesti ditekan dan banyak hak-haknya diabaikan. Populasi Indonesia yang banyak dan menganggur (“bonus demografi”), adalah potensi eksploitasi yang tidak dapat dilewatkan. Padahal, mesin produksi telah diotomatisasi dan serapan tenaga kerja jelas jauh menyusut. Ini yang rentan memperuncing konflik horizontal dan sentimen rasial akibat rebutan lapangan pekerjaan. Orang-orang setempat menganggur sementara kekayaan alamnya dijarah dan lapangan pekerjaan menyerap para pendatang yang punya akses istimewa karena lebih “terdidik” atau dianggap lebih rajin. Stigma penduduk lokal adalah pemalas merupakan warisan kolonialisme.
Di sektor paling hulu, sumber daya tambang, perkebunan dan hutan harus dikeruk semaksimal mungkin. Orang-orang di desa akan menelantarkan ekonomi subsisten mereka untuk mengejar standar “kemajuan”: rumah dari beton, kerja upahan, televisi dan mobil, anak yang berkuliah ke kota. Di saat bersamaan, lahan pertanian dan hutan adat mereka perlu dirampas secara paksa, dan itu sering dengan kekuatan bersenjata dan perlawanan yang berdarah-darah. Ini akan menghasilkan lubang-lubang raksasa dan perkebunan monokultur yang merusak tidak hanya keanekaragaman bioregion, tetapi juga pranata kehidupan lokal.
Ketika pabrik-pabrik didirikan, kawasan industri yang suram di Jawa menyasar hamparan areal persawahan yang luas yang dulu menjadi andalan bagi pasokan pangan regional. Gangguan di pedesaan bukanlah wereng atau tikus, tapi partikel berbahaya limbah udara dan cair. Untuk menopang industri itulah maka puluhan PLTU batubara dibangun di seluruh penjuru Indonesia. Tujuannya bukan untuk memberikan penerangan bagi perkampungan yang dari dulu memang diabaikan oleh pemerintah, tetapi suplai energi untuk kebutuhan industri yang sedang digenjot.
Ketika pabrik-pabrik semakin banyak, produksi berlanjut. Kenyataannya, kita telah memasuki suatu era yang disebut sebagai “pasca-kelangkaan” (post-scarcity), yaitu situasi over-produksi, dimana kita telah menghasilkan terlalu banyak barang, yang sebenarnya lebih dari cukup dari yang kita butuhkan. Penumpukan produksi di gudang dan harga menjadi murah tidak akan berujung pada pembagian gratis barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk yang banyak berarti celah pasar yang banyak pula, dan kita akan diarahkan pada konsumsi gila-gilaan pada barang yang tidak kita butuhkan atau sebenarnya bisa kita gunakan secara kolektif (seperti motor, televisi, telepon genggam, mesin cuci, alat-alat pertukangan, dst). Produk kerajinan tangan yang artisitik skala kecil, kalah dan kita semakin dimanjakan untuk membeli ketimbang menghasilkannya sendiri. Kontradiksinya, orang- orang sengaja dikondisikan miskin tetapi belum tentu dapat mengakses kekayaan sosial tersebut. Pertimbangkan pula bahwa semakin banyak kita mengkonsumsi produk industri, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Ini, berakar dari produksi, bukan konsumsi.
Situasinya hampir sama buruk di kampung dan di kota. Tetapi lebih banyak orang “miskin” kampung yang ke kota ketimbang sebaliknya. Ini berujung pada urbanisasi dan pertumbuhan sabuk perkotaan. Kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan harga jual tanah. Wilayah perkampungan kota harus digusur untuk kepentingan pengusaha. Orang-orang miskin dan buruh kantoran akan berada di wilayah baru pinggir kota atau terjepit di kawasan kumuh perkotaan yang semakin menyusut. Ini menciptakan kontras visual antara kehidupan yang benar-benar sekarat dengan kemewahan dan kehidupan yang berlimpah ruah. Akan semakin banyak wilayah dimana orang-orang miskin dilarang masuk, bahkan di tempat-tempat publik mereka tidak boleh terlihat (harus disembunyikan). Penyingkiran ini berarti perluasan sabuk perkotaan, membuat denyut transportasi keluar-masuk kota menjadi dapat ditebak: pagi yang macet dari rombongan pekerja ke pusat kota, sore yang macet untuk pulang ke pinggir kota. Ini akan jadi problem transportasi yang akan sangat sulit dan mahal untuk dipecahkan (belum biaya bahan bakar, kecelakaan transportasi dan gangguan kesehatan men- tal dari robot-robot tak bernyawa akibat rutinitas kejam).
Di satu sisi, peradaban kota yang semakin besar tidak dapat didukung oleh bentuk-bentuk sumber energi terbaru- kan seperti panel surya dan mikrohidro yang berskala kecil dan memproduksi energi secara terbatas. Akibatnya, PLTU (dan mungkin kelak nuklir yang sangat berbahaya) harus dikerahkan karena ia semakin sesuai dengan kebutuhan atas energi raksasa untuk kawasan populasi yang terpusat. Birokrasi tidak berminat untuk inisiatif skala kecil yang merepotkan dan sebenarnya tidak menguntungkan pengusaha.
Jika semuanya dirunut, ini berujung pada regionalisasi ekstrim. Kawasan hutan disulap jadi tambang dan perkebubunan, kawasan pertanian harus diindustrialisasi dan petani skala kecil semakin tersingkir: dan metropolitan jadi pusat populasi melimpah, tapi tanpa tanah atau alat-alat produksi, sehingga mereka tidak menghasilkan apapun selain “pengangguran”, pekerja paruh waktu atau budak kapital. Padahal gaya hidup beradab mereka harus ditopang dari pengorbanan besar di luar kawasan urban. Bahan baku untuk produksi pabrik, tambang untuk energi listrik, dan pangan penduduk perkotaan perlu diangkut dengan masif, yang membutuhkan perluasan jaringan jalan raya dan daya angkut raksasa (dengan resiko raksasa, termasuk tumpahan minyak bumi, hewan liar yang jalur migrasinya terputus, pemukiman yang semakin merapat ke pinggir jalan karena prospek ekonomi yang lebih menjanjikan dan akses terhadap materi kehidupan beradab).
Seluruh proses ini pada akhirnya mengarah pada peningkatan karbon, perubahan iklam yang ekstrim, kekeringan dan kenaikan permukaan laut. Bookchin telah memperingatkan semua ini hampir setengah abad yang lalu dan distopia yang ia tulis benar-benar terwujud. Situasi mendesak hari ini justru membuat gagasan dan usulan Bookchin perlu dipertimbangkan lebih serius. Usulannya tidak perlu diulang-ulang, tetapi perlu disinggung kembali secara ringkas di sini.
Selain menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dan gila-gilaan, kota perlu diatur ulang hingga ke taraf yang lebih manusiawi. Itu berarti komunitas yang lebih terdesentralisir, otonom satu sama lain, dan terkonfederasi. Alih-alih negara dengan birokrasi yang terpusat, ia menyaratkan demokrasi langsung tatap muka ala polis Yunani kuno. Masyarakat kota harus dikurangi ukurannya dan tersebar luas di atas tanah, itu artinya berskala sedang atau kecil dan menolak pemusatan populasi yang berlebihan karena ber- ujung pada aparatur birokrasi yang tidak manusiawi, alienasi akut, dan solidaritas sosial yang rendah. Komunitas berskala kecil memungkinkan rasa saling kenal, kepedulian dan percaya yang lebih besar. Ini juga berpengaruh terhadap mekanisme pengambilan keputusan, keamanan dan pengadilan yang lebih baik dan otonom. Masyarakat mengendalikan diri mereka sendiri (self-governance).
Dalam komunitas otonom itulah kita bisa mengandalkan sumber energi yang lebih beragam. Panel surya di daerah panas, turbin angin di daerah pegunungan, atau mikrohidro di pedalaman sungai. Dalam kebutuhan yang kecil, maka ada keberlanjutan tenaga energi. Bookchin percaya bahwa otonomi juga akan menciptakan keserasian karena setiap komunitas akan kembali menyesuaikan kebutuhan diri dengan lingkungannya alih-alih kebijakan negara yang terpusat. Kebijakan negara memang secara intrinstik anti-ekologi. Misalnya, standar kemiskinan atau pangan nasional. Mengapa orang Dayak dulu disebut terbelakang, karena mereka menggunakan kayu besi yang tersedia di hutan sebagai material bangunan rumah panjang kolektif mereka yang ramah lingkungan? Mengapa mereka dianjurkan untuk membangun rumah individual dari beton? Atau, bukankah tidak semua daerah di Indonesia dulu mengandalkan beras? Mengapa food estate justru diciptakan di Papua dimana sawah malah menyasar hamparan pohon sagu? Kita tidak perlu kaget ketika mencari tahu siapa yang paling diuntungkan dari standarisasi papan dan pangan ini. Pada masa Orde Baru, pohon raksasa berumur hampir lima ratus tahun dihabiskan dan keberagaman pangan hancur akibat Revolusi Hijau. Kebijakan negara itu cenderung memukulrata keberagaman bukan karena birokrasinya bodoh, tapi homogenisasi itu diperlukan dan menguntungkan elit tertentu. Kita bisa mengeksplorasi banyak kebijakan semacam ini, dan hasilnya adalah pengulangan yang sama (sebut saja kurikulum pendidikan).
Karena itu Ekologi Sosial berarti anti-negara dan anti-kapitalisme. Di situlah anarkismenya.
Bookchin menuliskan semua itu dalam suasana yang sangat optimistik dalam konteks sejarah dimana gerakan perdamaian tahun 1960'an sedang meningkat, Komunisme Internasional sedang bangkrut, dan isu lingkungan mulai mendapatkan perhatian publik. Tetapi ia dan gagasannya tidak luput pula jadi sasaran kritik.
David Graeber dalam Fragments of Anarchist Anthropology juga setuju dengan demokrasi tanpa negara, sebab banyak masyarakat anarkis-primitif yang menerapkannya. Hanya saja ia berseberangan dengan Bookchin dalam perkara contoh demokrasinya. Bookchin dianggap sengaja mengabaikan bentuk politik demokrasi yang non-Eropa dan memilih Yunani yang justru bersifat mayoritarian (artinya, keputusan sering diambil dari suara terbanyak). Padahal, demokrasi konsensus (musyawarah untuk mufakat) ada di seluruh muka bumi. Itu hal lumrah di banyak wilayah nusantara, misal. Tetapi Bookchin hanya berkutat pada polis Yunani kuno yang cenderung hirarkis karena perbudakan atau patriarki.
Berangkat dari politik federalisme ala Proudhon dan komunisme Marxis, Bookchin juga mengusulkan sistem ekonomi yang menekankan pada produksi sesuai dengan kebutuhan, bukan keuntungan, serta akses yang merata kepada hasil produksi. Di saat bersamaan, pabrik-pabrik perlu dikuasai oleh buruh di bawah kendali majelis warga. Asumsinya, jika masyarakat setempat punya kendali atas keberadaan pabrik, mereka punya kuasa untuk mengatur kapan atau bagaimana pabrik tersebut berfungsi. Ini termasuk meminimalisir potensi kerusakan akibat berfungsinya mesin-mesin itu, (limbah misalnya, yang biasanya dibuang di sekitar pabrik dan masyarakat setempat yang justru terkena imbasnya).
Yang jadi masalah, pabrik dan mesin yang merusak itu tetap mesin yang sama apapun sistem politiknya. Tidak detail, sejauh yang saya tahu, usulan Bookchin soal masalah ini. Tapi secara tidak langsung, tampaknya Bookchin hingga batas tertentu setuju dengan deindustrialisasi ketika menyatakan bahwa krisis ekologis merupakan kontradiksi antara pengrajin dan industri massal. “Ini berarti mengganti tenaga kerja tanpa henti dengan pekerjaan kreatif dan penekanan pada keahlian kerajinan tangan yang artistik dalam memilih produksi mekanis,” tulisnya. Tampaknya, bakal ada banyak mesin dan pabrik yang memproduksi secara massal barang-barang yang tidak ramah lingkungan yang sebenarnya bisa kita hasilkan sendiri, yang mungkin perlu ditutup. Setidaknya, ia setuju dengan “kombinasi penggunaan kerajinan tangan dan mesin yang sangat serbaguna, otomatis, dan canggih untuk mengurangi kerja keras manusia dan orang-orang menjadi bebas untuk mengembangkan diri sebagai penduduk yang kreatif dan yang terinformasi.”
Seperti saya bilang, anarko-indigenisme belum berkembang pada sebagian besar hidup Bookchin, dan bahkan walau literaturnya telah dihasilkan, tampaknya itu tidak sampai di tangannya atau Bookchin memang mengabaikannya. Pantas dan masuk akal jika ia menolak kecenderungan mistik dari gerakan ekologi. Tetapi pemahaman kita yang semakin dalam atas masyarakat adat menunjukkan bahwa banyak dari pranata atau kepercayaan tradisional itu berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan-hutan keramat yang tidak boleh disentuh sama sekali, atau tanah ulayat warisan leluhur, atau dewa-dewi peri-peri pelindung bumi). Ini bisa menjadi senjata konservasi, tanpa mengenyampingkan sains yang oleh “ekologi mistik” (julukannya Bookchin) sering lihat secara sinis sebagai penyebab perusakan lingkungan.
Saking berkomitmennya terhadap perubahan struktural, ia mengabaikan perubahan (baca: kepentingan) personal yang saat ini justru semakin relevan. “Anarkisme individualis sebagian besar tetap merupakan gaya hidup bohemian, tuntutannya yang paling mencolok adalah kebebasan seksual ('cinta bebas') dan terpikat pada inovasi dalam seni, perilaku, dan pakaian,” tulis Bookchin dengan pedas pada 1995. Waktu itu ia sedang kesal dengan para anarko-primitifis. Ia menyebut tradisi individualis yang mengutamakan otonomi individual ketimbang kebebasan sosial, sikap tidak disiplin, penolakan terhadap organisasi dan program, serta kecenderungan untuk terlibat dalam terorisme, sebagai “anarkisme gaya hidup” (life- style anarchism). Kritiknya jadi terlalu meluas dan adhominem. Ini membuat gagasannya semakin berbenturan dengan banyak tradisi individualis dan egois yang semakin meningkat pada dekade 90'an hingga saat ini, yang kemudian membuatnya menyerah dengan anarkisme dan menyebut idenya seba gai Komunalisme. Subjudul tulisan tersebut, “Jurang yang Tak Terjembatani”, sekaligus memposisikan dirinya sebagai kolektivis ekstrim, yang dengan tegas menyatakan bahwa kebebasan sosial harus ada di atas otonomi individu. Jelas ini pengkhianatan besar bagi anarkisme dimana yang sosial dan personal biasanya dianggap mesti berjalan berbarengan.
Ia punya privillege sebagai akademisi yang kebutuhan hidupnya terpenuhi dan perutnya buncit, hidup di kota kecil yang relatif sejuk, disayangi oleh para pengikutnya, dan menyenangkan serta memuaskan dirinya untuk membaca dan menulis. Bookchin tidak peka terhadap bagaimana tiap orang pada tiap zaman akan merespon secara berbeda dominasi dan eksploitasi yang bisa jauh lebih kejam dan mengerikan: kemiskinan dan kelaparan akut, atomatisasi ekstrim, alienasi satu sama lain, konsumerisme hampa bahwa bahagia berarti lebih banyak membeli atau unsur-unsur merusak kegilaan peradaban yang membuat seseorang sungguh dapat kehilangan kewarasannya. Cukup mengutip Raul Vaneigem: “Mereka yang bicara tentang revolusi dan perjuangan kelas dengan merujuk pada hidup sehari-hari, tetapi tanpa memahami daya subversif cinta dan hal-hal positif yang timbul dari penolakan akan kekangan, sesungguhnya mulut mereka bau bangkai!.”
Militansi dan komitmen organisasional untuk revolusi sosial yang ditekankan Bookchin kerap tidak cocok dan dianggap membosankan bagi banyak semangat pemuda yang semakin beralih pada kepuasaan personal ketimbang perubahan sosial “yang lebih baik” (yang belum terwujud-wujud juga). Optimisme Bookchin sebenarnya bisa dibilang terlalu kejam, dan mungkin ia masih terpengaruh tradisi marxis yang dulu dipeluknya.
Ketika ia mulai menulis tentang ekologi pada 1960'an, populasi manusia di bumi mencapai 3 milyar. Jumlah tersebut meledak menjadi lebih dari dua kali lipat menjadi 7,7 milyar pada 2020. Ini artinya, kita mesti berhati-hati dalam membaca tulisan-tulisannya yang kerap menyepelekan tingginya populasi manusia yang, mungkin, sebenarnya saat ini telah mencapai proporsi hama karena berkontribusi atas pengurasan besar-besaran sumber daya bumi yang tidak mampu menampungnya lagi. Manusia sebanyak itu menyaratkan industrialisasi pertanian dan peternakan skala raksasa. Apakah pertanian organik dan non-monokultur, yang beragam, terdesentralisasi dan berskala kecil seperti diusulkan Bookchin itu, tetap dapat memenuhi syarat tentang utopia masyarakat ekologis dimana dunia sosial manusia berjalan harmonis dengan dunia alam? Saya masih ragu-ragu untuk menjawabnya. Tapi saya tidak menampik bahwa itu adalah pilihan terbaik ketimbang berburu-meramu yang hanya dapat mengakomodir jumlah manusia dalam populasi kecil (Yang entah harus dikemanakan manusia yang ada sebanyak ini sekarang? Mati dalam kehancuran peradaban kah?) atau industri pertanian dengan agen-agen kimia dan penuh resiko. Komunitas skala kecil yang tersebar tampaknya harus didukung pula oleh pengurangan populasi manusia, hingga ke jumlah yang entah bagaimana, komunitas itu sendiri yang paling mengerti untuk menentukannya berdasarkan situasi lingkungannya sendiri.
Selain itu, kita telah menghasilkan lebih banyak sampah hari ini, dan sampah itu kadung tersebar. Bahkan ketika katakan saja revolusi berhasil, kita harus berhadapan dengan sampah-sampah tersebut. Penyepelean Bookchin terhadap anti-konsumerisme dan daur ulang sampah pada dekade 60'an itu justru berbahaya hari ini. Jadi, Ekologi Sosial harus berkembang dari yang sebelumnya terlalu menekankan pada perubahan struktural, termasuk pada yang sifatnya personal. Gaya hidup ramah lingkungan atau menanam pohon, salah satunya, sama radikalnya dengan membangun majelis warga, pertempuran jalanan, atau pemogokan buruh. Dari Spanyol 1936 hingga Rojava, penanaman pohon telah dilakukan bahkan oleh anarkis. Memang, kita tidak boleh puas dan berhenti hanya sampai di situ. Kita jadi butuh lebih banyak orang dan lebih banyak keberagaman taktik dan metode.
Bookchin yakin bahwa kerusakan ekologi kelak menjadi tidak dapat ditolerir lagi dan membuat orang-orang memberontak: sementara itu Alfredo Bonanno percaya bahwa di masa mendatang akan lebih banyak jenis kerusuhan yang semakin irasional ke depannya, akibat “perasaan tidak berguna, dari kebosanan, dan dari atmosfir ghetto yang mematikan.” Jika atmosfir yang dimaksud Bonanno dapat dimaknai dari kondisi kumuh, suram dan penuh limbah peradaban kota, maka bisa jadi ada sedikit kesepakatan antara keduanya. Jadi ada sebab-akibat di sini. Masalah sosial (hierarki, dominasi dan eksploitasi), berujung pada masalah ekologis, yang menyebabkan lebih banyak masalah sosial lain. Misal, perbatasan negara semakin diperebutkan karena upaya penjarahan besar-besaran terakhir, dan ini memicu perang bilateral dua negara. Kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan bencana alam (yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari negara dan kapitalisme), dapat memicu kerusuhan, perang sipil, krisis migrasi, dan konflik ras. Bonanno mengusulkan supaya kerusuhan yang sifatnya irasional itu harus diarahkan menjadi insureksi terhadap tatanan yang ada.
Pemberontakan itu akan tiba dan semakin banyak. Tapi kapan?
Populasi raksasa manusia yang hidup di ujung nadir keruntuhan peradaban ini juga menghasilkan pesimisme luar biasa soal bagaimana kampanye Ekologi Sosial (dan sebenarnya seluruh proposal utopis lain) akan berhasil. Hegemoni negara dan kapital begitu kuat, dan yang hidup saat ini banyak yang hanya mengais atau menjarah segala yang tersisa di bumi (menjual air yang tersedia gratis saja sudah hal yang absurd, tapi udara bersih pernah dijual di Cina pada masa- masa paling parah polusi udara akibat industri mereka). Bisa jadi, kapitalisme dan negara hancur karena perbuatannya sendiri yang semakin tak terkendali, tetapi kehancurannya menyeret bumi dan seluruh yang hidup didalamnya. Siapa yang tahu? Saya sedang berbicara tentang sintesis antara Ekologi Sosial dan anarko-primitifisme, yaitu masyarakat pasca-kiamat (post-apocalypse). Tesisnya mesti berangkat dari: bagaimana jika agenda perjuangan itu gagal, bumi keburu hancur?
Saya bisa saja dicap fatalisme dan nihilistik. “Tetapi ketimbang menjalani hidup untuk menunggu kebangkitan massa yang sepertinya tidak akan pernah terjadi, maka lebih baik untuk menyerang sekarang dan lihat kemana tindakan tersebut membawa kita,” tulis Serafinski. Ini kalimat yang inspiratif sekaligus berbahaya. Namun walau anda berdiam diri dalam kepasrahan, bahaya tetap ada di sekitar anda dan justru akan mendatangi anda dengan sendirinya, cepat atau lambat. Krisis ekologis dan sistem eksploitasi itu saja sudah begitu merusak tubuh dan jiwa kita, yang mendesak pemberontakan dan kehancuran tatanan itu, sekarang.
Ide-ide dasar Ekologi Sosial coba diterapkan sejak 2013 di Suriah oleh orang-orang Kurdi melalui administrasi Konfederalisme Demokratik (populer disebut Rojava) yang menjadikan feminisme, ekologi dan demokrasi langsung sebagai pilarnya. Bapak ideologisnya, Abdullah Ocalan, mengklaim ia terinspirasi dari Murray Bookchin. Betul, Bookchin mengusulkan supaya munisipalisme libertarian diwujudkan melalui politik elektoralisme lokal, yang kemudian melegalkan dewan atau majelis warga. Kelak, warga kota dan negara akan berada dalam puncak ketegangannya, kekuasaan ganda. Ini harus berujung dimana yang satu mengalahkan yang lain.
Tetapi munisipalisme libertarian tidak naif. Mereka juga mengusulkan milisi bersenjata. “Munisipalisme libertarian, sebagai bagian dari tradisi sosialis dan anarkis, karenanya menyerukan pembentukan milisi sipil, atau tentara sipil, untuk menggantikan polisi dan angkatan militer. Milisi sipil ini akan berada di bawah pengawasan ketat majelis warga,” tulis Janet Biehl.
Bagaimanapun juga, kesempatan di Rojava diraih justru di tengah perang sipil Suriah melalui pemberontakan bersenjata, persis ketika oposisi menyerang rezim Assad dan para jihadis ISIS mendeklarasikan negara Islam. Segera setelah itu, komune-komune diorganisir, dan konstitusinya ditetapkan. Ada lebih banyak apresiasi ketimbang kritik. Tapi situasinya agak kompleks, khususnya karena mereka menerima bantuan persenjataan, pelatihan dan perlindungan udara dari Pentagon sebagai upaya memerangi ISIS (karena solidaritas internasional dari kaum revolusioner sendiri saat ini tidak dapat diandalkan, meski penampungan migran Suriah oleh anarkis Eropa serta milisi sukarela internasional yang berangkat berperang ke Suriah harus dihargai). Ingat, mereka sedang menghadapi salah satu kelompok ideologi paling militan di Timur Tengah hari ini, dan mereka berhasil, meski dengan serangkaian kompromi.
Kita perlu menjadikan Rojava sebagai studi kasus Ekologi Sosial yang menarik. Mereka tetap menanam pohon, mengkolektivisasi lahan pertanian secara sukarela, dan memperkuat pertahanan sipil. Eksperimen terus dicoba, pemberontakan terjadi kapan dan dimana saja. Situasi eksperimen politik Bookchin di Vermont dan diterimanya proposal Ekologi Sosial di Suriah berada dalam situasi dan kondisi yang berbeda yang perlu dianalisis. Sesuatu yang tidak dapat saya lakukan di sini.
Bagaimanapun juga, “kita tidak boleh pelit dalam melepas imajinasi manusia,” tulis Bookchin. Benar. Jadi, mari kita mulai membayangkan, menghancurkan dan menciptakan kembali. Ekologi Sosial, filsafat naturalisme dan politik Munisipalisme Libertarian Murray Bookchin menyediakan titik berangkat yang menarik dan patut diperhitungkan. Pilihannya tidak banyak dan mendesak kita untuk mendiskusikan dan mengorganisir sekarang. Saya menekankan bahwa tindakan kecil perlu digabungkan dengan upaya pengorganisiran jangka panjang pula.
