Bima Satria Putra
Multatuli dan Kecenderungan Anarkisme
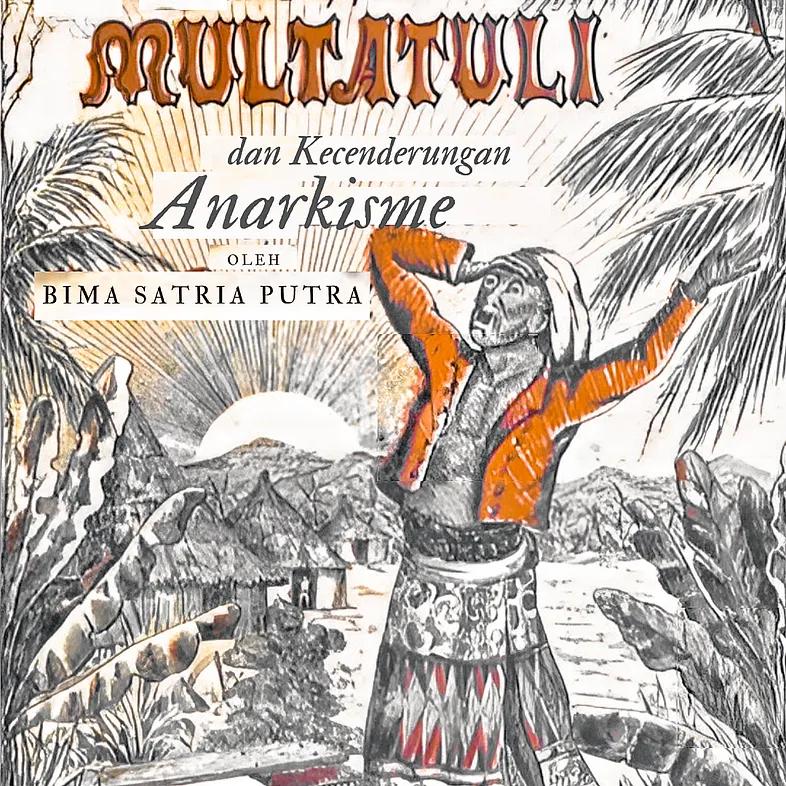
Suatu kali, penulis Indonesia Y.B. Mangunwijaya dalam sebuah wawancara di tahun 1980’an pernah ditanyai tentang siapa penulis favoritnya. Mangunwijaya menyebut dua nama: Pramoedya Ananta Toer dan kemudian Multatuli. Lalu pewawancara dengan polosnya melontarkan pertanyaan tidak terduga, “Bagaimana dengan penulis asing?”—dipikirnya, Multatuli adalah penulis Indonesia.[1]
Multatuli memang menempati posisi yang rada ambivalen. Ia seolah bermain dengan dua kaki, antara yang asing dan yang pribumi. Ada ketertarikan sekaligus penolakan yang nyaris simultan. Dari sisi yang lebih ekstrem, seperti pada 2017 misalnya, puluhan mahasiswa Lebak memprotes penggunaan nama Multatuli yang semakin marak. “Sebaik-baiknya penjajah tetap saja penjajah,” ujar mereka. Di Kabupaten Lebak, Banten, namanya memang bertebaran. Ia dijadikan nama jalan, gedung pertemuan, perusahaan air minum daerah, hingga museum.
Saya tidak tertarik untuk melakukan kajian sastra pasca-kolonial tentang tempat Multatuli dalam masyarakat Indonesia. Pembingkaian semacam ini sudah sering dilakukan. Sebaliknya, saya ingin biarkan Multatuli berbicara dari penanya sendiri, tentang gagasannya dan tentang bagaimana ia menempatkan dirinya.
Nama aslinya adalah Eduard Douwes Dekker. Ia pertama kali pergi berlayar ke Hindia pada 1838 dan tidak lama kemudian bergabung dalam dinas koloni. Setelah beberapa kali berpindah dinas, Eduard diangkat sebagai Asisten Residen di Lebak, Banten (1856). Bertekad untuk mengungkap skandal yang disaksikannya selama bertahun-tahun di Hindia Belanda, Eduard menulis novel berjudul Max Havelaar yang terbit pada 1860. Ia menggunakan nama penulis dari frasa Latin, Multatuli (secara harfiah berarti: “Aku Sangat Menderita”). Ia terkenal dengan nama itu dan terus menggunakannya dalam berbagai tulisannya kelak.
Max Havelaar, tokoh utama dalam novel, adalah seorang pegawai sipil Belanda di Jawa. Ia terbakar amarah sendirian karena idealismenya untuk mengakhiri perlakuan buruk dan penindasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kolonial dan pejabat pribumi lokal terhadap penduduk. Bupati dan camat, terlibat dalam “pemerasan” yang brutal dengan menyita kerbau para petani tanpa imbalan yang sepantasnya. Max yang murah hati mencoba memberikan kompensasi dari uangnya sendiri dan hal ini malah menjerumuskan dirinya pada hutang. Ia juga mencoba melaporkan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi tidak digubris.
Satu per satu, tiap langkah Max malah mengubah situasi dari buruk menjadi petaka yang menjatuhkan kariernya. Max mundur dari pekerjaannya (dalam keadaan miskin), lalu menuliskan kisahnya. Pada bagian akhir, sang pengarang Multatuli hampir membawa (dan mengaburkan) karangan ke dalam kenyataan, saat ia muncul sebagai dirinya sendiri dan menyerukan, “pertolongan dan bantuan...dengan kekerasan atas jalan yang sah, jika perlu.”[2]
Novel Max Havelaar mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa ketika pertama diterbitkan dan mendorong kaum liberal untuk reformasi “politik etis” demi kesejahteraan di Jawa. Ia menginspirasi satu generasi intelektual mulai dari Karl Marx (tapi tidak sebaliknya), Hermann Hesse, Sigmund Freud dan banyak tokoh dari beragam spektrum politik, mulai dari sosialis, nasionalis, liberal, dan terutama anarkis.
Anarko-sindikalis Jerman Rudolf Rocker, yang juga menjadi sekretaris IWA, memuji karya tersebut dan menjabarkan kecenderungan libertarian Max Havelaar dalam tulisannya, Multatuli: An Anarchist Seer (1933) yang terbit di majalah anarkis Freedom di London. Anarkis Rusia Peter Kropotkin pernah menjajarkan Multatuli dengan Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry David Thoreau, dan Henrik Ibsen. Karya-karya mereka, tulis Kropotkin, “penuh dengan gagasan yang menunjukkan betapa eratnya anarkisme terjalin dengan karya yang sedang berlangsung dalam pemikiran modern ke arah yang sama dengan pemulihan hak manusia dari jerat negara dan kapitalisme.”[3]
Apresiasi muncul dari banyak kelompok, tetapi anarkis jadi yang paling giat menerjemahkan dan mempromosikan karya ini dalam berbagai bahasa utama dunia.[4] Terjemahan bahasa Jerman dikerjakan oleh Wilhelm Spohr yang bergerak dalam lingkaran kaum anarkis Jerman. Terjemahan bahasa Perancis dikerjakan anarkis: yang pertama terbit pada 1876 berkat A.J. Nieuwenhuis dan kemudian oleh anarkis Belanda Alexander Cohen pada 1901.
Pada gilirannya, terjemahan mereka ini diterbitkan ulang atau dijadikan rujukan dalam penerjemahan di berbagai negara lain. Terjemahan Cohen mendorong terjemahan kedua dalam bahasa Inggris yang terbit pada 1927 oleh Willem Siebenhaar, anarkis Belanda yang pergi ke Australia pada 1891. Terjemahan Willem Siebenhaar nantinya diterbitkan di Amerika Serikat oleh Knoopf di New York. Sementara terjemahan Spohr sempat diduga menjadi teks perantara untuk diterjemahkan kembali ke bahasa Rusia.[5] Sastrawan anarkis Felipe Alaiz de Pablo sangat terinspirasi oleh Multatuli dan jadi yang pertama mengenalkan karya ini di Spanyol dan Meksiko.[6] Surat kabar anarkis Yahudi Arbeter fraynd [Sahabat Buruh] di London juga mengiklankan terjemahan bahasa Ibrani dalam suplemen sastra mereka.[7]

Meski beberapa penulis mengklaim Multatuli sebagai anarkis,[8] Eduard Douwes Dekker sendiri tidak pernah secara terbuka menyatakan diri anarkis. Sebenarnya, Multatuli mulanya lebih mirip sebagai seorang despotik. Jika administrasi Kerajaan Belanda ingin mendapatkan kembali rasa keadilannya, maka hal itu dapat dilakukan dengan memberi penghargaan kepada Multatuli atas kritik dan tindakan gegabahnya. Selain itu, keadilan ini diwujudkan dengan memberikannya jabatan dengan kekuatan yang cukup (atau absolut), untuk menangani para pemimpin pribumi dan musuh-musuhnya dalam pemerintahan kolonial Belanda yang “korup”, untuk selama-lamanya.
Multatuli sebenarnya punya rencana. Dengan kekuasaan, Multatuli merasa dapat memperbaiki keadaan di Hindia. Pada 1876, Multatuli menulis:
“Saya seorang lalim berdasarkan rancangan, berdasarkan perhitungan, dengan sengaja. Saya telah memaksakan ciri-ciri sifat itu pada diri saya karena saya sampai pada kesimpulan, setelah pengamatan terus-menerus dan pemikiran yang mendalam, bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan apa pun... Hindia butuh dua ratus hingga tiga ratus tahun untuk bentuk pemerintahan yang menyerupai feodalisme. Tapi sebelum [bentuk pemerintahan] yang lain muncul, organisasi macam ini mesti berwujud despotisme tak terbatas [sic].”[9]
Kritik Multatuli diarahkan supaya ia mendapatkan jabatan, dan memang itu yang ia lakukan. Ketika pemerintah mulai khawatir dengan novel kritis itu, Multatuli ambil kesempatan ini untuk mengajukan tuntutan. Pertama, ia ingin kenaikan pangkat (menjadi Residen, dan kemudian Anggota Dewan Hindia). Selain itu, ia meminta sejumlah besar uang dan medali bergengsi untuk mengakui jasanya. Dengan semua ini ia percaya diri dapat melakukan perubahan di Hindia.
“Aku sangat menderita” artinya bukanlah ekspresi ketidakadilan pemerintah pada penduduk, tetapi pada dirinya sendiri. Max Havelaar dengan demikian bukan novel anti-kolonial. Multatuli sendiri tidak mengkritik sistem tanam paksa. Sebaliknya ia mendorong reformasi penyelenggaraan kolonialisme yang lebih baik. Multatuli pernah bilang ia “tidak menantang hukum dan ketertiban, tetapi menentang pelecehan atas hukum dan ketertiban.”[10]
Kalau begitu, gairah macam apa yang menjadi tenaga penggerak anarkis zaman itu untuk penyebarluasan Max Havelaar? Apa yang menjelaskan kedekatan karya Multatuli dengan anarkisme?
Sosialis dan teoretikus Marxis, Frank van der Goes, menyatakan Multatuli sangat berpengaruh di kalangan sosialis dan anarkis di Belanda, karena secara “kebetulan, semua yang merupakan bagian dari inti teori anarkis, ada dalam karya-karyanya.” Ia dengan sinis menjuluki Multatuli sebagai “patron anarkis di Belanda.”[11]
Simpati para anarkis pada Multatuli punya dasar yang kuat. Multatuli memang tidak menyebut dirinya sosialis dalam pengertian politik partai (sebagaimana ia tidak ingin disebut liberal atau konservatif), tetapi pada masanya ia memang memiliki pemikiran bernada sosialis. Misalnya, ia menyerukan perbaikan posisi buruh dan perempuan, serta kenaikan gaji guru. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kaum sosialis menganggapnya punya roh yang sama.
Meski mulanya ia adalah seorang kolonial romantis yang haus kekuasaan, Multatuli pelan-pelan semakin radikal. Ia berulang kali menentang campur tangan pemerintah dalam pendidikan dan wajib vaksin. Dalam sepucuk surat kepada H.C. Muller tertanggal 15 Agustus 1886, Multatuli juga menyatakan bahwa dirinya bukan sosialis dan bahkan anti-sosialisme, karena menurutnya kaum sosialis ingin membuat Negara jadi 'Mahakuasa’. Dia melanjutkan:
“Saya sebisa mungkin mendesak berkurangnya campur tangan Kejahatan yang disebut sebagai ‘Pemerintah’. Kaum sosialis terus-menerus membela dan mendorong undang-undang baru, sementara saya berpendapat bahwa seseorang terutama mesti mendorong penghapusan undang-undang.”[12]
Gagasan Multatuli mendapatkan dukungan dari kawan karibnya. “Aku, sama sepertimu, juga mendukung campur tangan minimal dari negara,” tulis Sikko Ernest Willem Roorda van Eysinga pada Multatuli.[13] Sama seperti Multatuli, sosialis Belanda yang lahir di Semarang itu, untuk waktu yang singkat pernah bekerja sebagai manajer perkebunan tembakau dan insinyur kereta api di Hindia. Selama bekerja ia menyaksikan kesengsaraan penduduk setempat. Pengalaman ini menginspirasinya untuk menerbitkan puisi di surat kabar Bataviaasch Handelsblad yang menyoroti kelaparan penduduk pribumi dengan judul, “Vloekzang, de laatste dag der Hollanders op Java door Sentot” [Lagu kutukan, hari terakhir orang Belanda di Jawa oleh Sentot]. Multatuli suka puisi ini dan memasukkannya dalam edisi keempat Max Havelaar pada 1875.
Menurut Eysinga, kaum sosialis dan anarkis terlalu absolut. Meski begitu, “setidaknya saya sedikit berharap pada kebahagiaan yang diramalkan oleh Louise Michel,” tulisnya. Baik Eysinga dan Multatuli tidak berhenti pada pemerintahan minimalis. Eysinga kemudian pindah ke Clarens, Swiss pada tahun 1881. Di sana dia berkenalan dengan kaum anarkis dan sosialis seperti Elie Reclus dan L. Metchnikoff. Yang paling terutama, Eysinga mulai jatuh cinta pada gagasan anarkis Prancis Pierre Joseph Proudhon. Dari Swiss ia juga menulis di surat kabar anarkis Le Revolté di Paris dan bersurat dengan Peter Kropotkin.
Multatuli, juga, bergerak ke arah yang sama. Dalam serial Ideen [Gagasan], Multatuli akhirnya menulis:
“Bentuk pemerintahan yang ideal adalah ketiadaan pemerintah. Apa yang memungkinkan pendekatan ideal itu? Berkurangnya kebutuhan rakyat untuk diperintah, yaitu: pembangunan, peradaban, pencerahan, dll. Jika masing-masing tahu apa yang harus dia lakukan, dan bertindak sesuai dengan itu, semua pemerintahan akan menjadi sia-sia.”[14]
Gagasan Multatuli di masa tuanya mendekati anarkisme secara politik. Tetapi E.M. Beekman, yang dengan gamblang menelanjangi Multatuli, dalam kata penutup Max Havelaar terjemahan Bahasa Inggris, telah menguraikan kecenderungan anarkis Multatuli kala mudanya secara filosofis. Menurut Beekman, Multatuli tidak punya rencana, program atau kebijakan bersama. Hal itu akan bertentangan dengan alur romantismenya. Seperti Byron, Multatuli adalah seorang pemberontak baheula, menentang sistem apa pun, baik itu pemerintahan, gereja, atau konvensi sosial. Dia mengagumi Voltaire justru karena dia tidak memiliki sistem. Multatuli menulis: “Voltaire adalah non entitas di mata para pengikut Kant, Hegel, Spinoza, Descartes, dan Leibnitz….. Mengapa? Karena dia tidak mengatakan apa pun yang tidak dapat dipahami semua orang, dan karena dia tidak menggabungkan sistem...”[15]
Kesan serupa, dengan cara berbeda, dibenarkan oleh Ferdinand Domela Nieuwenhuis di dalam memoarnya, Van Christen tot Anarchist (1910). Domela adalah seorang pastor, berubah menjadi ateis yang garang. Ironisnya Domela tampil sebagai juru selamat bagi buruh Belanda. Ia sering diilustrasikan sebagai Yesus di surat kabar karena kemampuan pengorganisiran yang baik saat ia memutuskan menjadi sosialis. Pada 1888, ia terpilih sebagai anggota dewan di parlemen dan menjadi wakil lantang untuk menyuarakan aspirasi buruh. Ia menyerukan penghapusan pekerja anak dan belanja paksa, hak pilih untuk perempuan, reformasi Kerajaan Belanda menjadi republik, dan bahkan kemerdekaan koloni Hindia dari Belanda beberapa dekade sebelum kelas intelektual Indonesia terbentuk!
Secara perlahan, ia mulai merasa bahwa aktivitas parlementer itu sia-sia dan ketertarikannya pada anarkisme semakin besar. Domela sempat bersurat dengan Multatuli tetapi baru pada 1886 berjumpa tatap muka. Multatuli menyatakan tidak setuju pada sosialisme, tetapi ia bersimpati pada ketekunan perjuangan Domela. Nah, bertahun-tahun kemudian saat Multatuli telah meninggal dunia dan Domela secara terbuka menyatakan diri sebagai anarkis, istrinya Multatuli berkata pada Domela, “kalian bakal lebih memahami satu sama lain sekarang!”[16]
Menurut Domela, kesalahannya Multatuli adalah ia hanya mengenal satu arus dalam sosialisme, yang berkaitan dengan disiplin, aturan dan parlemen. “Namun, andai ia mengenal anarki, yaitu sosialisme yang mencintai kebebasan,” tulis Domela, “dia pasti bakal berpikir sangat berbeda.” Dalam hal ini, Domela salah kira. Multatuli justru telah mawas anarki lebih awal. Dalam suratnya pada John F. Snelleman di tahun yang sama saat bertemu Domela, Multatuli meminta agar ia dikirimi tulisannya Peter Kropotkin.[17] Jelas di mata Multatuli, ketidaksetujuannya pada Domela diarahkan pada pandangan bahwa Domela adalah seorang naif yang percaya pada perubahan kebijakan dan perebutan kekuasaan.
Pada 2018, saya coba menerangkan sekilas kecenderungan anarkisme Multatuli. Tapi baru kali ini saya punya kesempatan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut pada tulisan dan korespondensinya. Tentu saja, di Indonesia, Multatuli tidak dikenal (di kalangan yang mengenalnya) sebagai anarkis, dan mungkin tetap demikian selama beberapa tahun ke depan. Multatuli yang dikenal Indonesia masih Multatuli-nya Max Havelaar yang 1860’an, bukan Multatuli dekade terakhir 1880’an. Max Havelaar sendiri baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1972 oleh H.B. Jassin, dan versi yang beredar baru-baru ini terjemahannya sangat buruk.
Multatuli menarik bagi saya bukan hanya karena ia punya kecenderungan anarkis. Lebih dari itu, saya tertarik pada kenyataan bahwa radikalisasi Multatuli justru terjadi di masa tuanya. Hal ini tidak hanya berlaku pada dirinya, tetapi pada banyak sosialis sezaman, seperti Eysinga dan Domela yang telah saya bahas. Saya sendiri secara terang-terangan mengklaim sebagai anarkis pada usia 21 tahun, dan saya sudah dicemooh (hampir seperti ramalan) oleh banyak orang bahwa saya bakal berubah dan berkompromi dengan tuntutan “sistem” pada usia 30 tahun. Itu artinya, ketundukan saya muncul sebelum rambut saya beruban.
Tampaknya zaman kita begitu berseberangan: ini adalah zaman di mana idealisme konon hanya dimonopoli kaum muda. Seiring berjalannya usia, idealisme itu diyakini bakal hilang. Padahal lebih dari seratus tahun silam, kecenderungan anarkisme Multatuli baru muncul di penghujung hayat, beberapa tahun sebelum kematiannya pada 1887. Hampir sepanjang jalan hidupnya, Multatuli adalah seorang pengkhayal kalau dirinya sebagai seorang kaisar di Indonesia (yang waktu itu ia sebut Insulinde). Multatuli naif bukan karena ia hendak menghancuran kekuasaan, tetapi karena bermimpi hendak merebutnya.
Multatuli juga penting bagi saya, karena ia membuat saya merenung. Bayangkan, Multatuli telah menginspirasi gerakan anti-kolonial global di dunia yang kolonial (hampir seluruh generasi aktivis gerakan kemerdekaan -Kartini, Tjipto Mangunkusumo, Tan Malaka, Soekarno, dsb, menyanjungnya). Anehnya, saat ini ia insignifikan. Saya tidak pernah bertemu satu pun mahasiswa yang mengatakan dirinya menjadi revolusioner setelah membaca Max Havelaar. Apakah ini artinya Multatuli tidak relevan bagi kita di Indonesia pasca-kemerdekaan?
Biar Anda simpulkan sendiri apakah kritik Multatuli pada struktur kolonial masih berguna di tengah konflik agraria di Pakel, di Tamansari, di Kendeng, Bara-Baraya, Kinipan, dan seluruh inci tanah “merdeka” ini. Saya pikir tidaklah berlebihan Mangunwijaya bilang dirinya terinspirasi Multatuli, saat menulis dalam novelnya Burung-Burung Manyar (1981):
“Ayahku dan aku dan Mami jauh lebih merdeka jiwanya daripada kaum Soekarno yang menghipnotis massa rakyat menjadi histeris dan mati konyol karena mengandalkan bambu runcing belaka melawan Mustang-mustang dan meriam-meriam Howitzer yang pernah mengalahkan tentara Kaisar Jepang. Maaf, Anda keliru alamat menamakan aku budak Belanda. Bagiku NICA hanya sarana seperti Republik bagi mereka sarana juga. Segala omong kosong tentang kemerdekaan itu slogan belaka yang menipu. Apa dikira orang desa dan orang-orang kampung akan lebih merdeka di bawah Merah Putih Republik Indonesia daripada di bawah mahkota Belanda? Merdeka mana, merdeka di bawah singgasana raja-raja Jawa mereka sendiri atau di bawah Hindia-Belanda?”
Di tengah krisis iklim, perampasan lahan, kriminalisasi petani dan masyarakat adat, rezim upah murah, hingga seluruh pengisapan dan penderitaan kita yang tampak tak berujung, Indonesia sebenarnya bisa jauh lebih kejam dari Belanda. Saya mengancam kelas penguasa zaman ini, menggunakan ancaman Multatuli pada kelas penguasa zaman itu: “dengan kekerasan atas jalan yang sah, jika perlu.” Berikan Multatuli kesempatan kedua untuk terlahir kembali, saya jamin ia sepenuhnya anarkis.
Bima Satria Putra adalah penulis dan peneliti sejarah independen. Tetap berkomitmen untuk menulis meski tengah menjalani 15 tahun hukuman penjara.

[1] Darren C. Zook, ‘Searching for Max Havelaar: Multatuli, Colonial History, and the Confusion of Empire’, dalam: mln 121 (2006), hlm. 1182.
[2] Eduard Douwes Dekker. Max Havelaar: Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda (1977), hlm 229.
[3] Peter Kropotkin, “Anarchism” (1910) dalam The Encyclopedia Britanica.
[4] Kajian tentang penerjemahan Max Havelaar, lihat: Baggio, Lucia. 2017. “Translating Multatuli: The reception of 'Max Havelaar' In Italy and the Rest of Europe.” Tidak diterbitkan.
[5] Grave, Jaap & Ekaterina Vekshina. “Max Havelaar van Multatuli in Rusland: het ontstaan van de vertalingen [Max Havelaar by Multatuli in Russia: The origins of translation]” dalam jurnal СКАНДИНАВСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ (SCANDINAVICA), Vol.19, No.1, Juni 2021. Hlm 176-189.
[6] Raemdonck, Anne van. “Felipe Alaíz de Pablo, de eerste 'Multatuli-fan' in Spanje” dalam jurnal Futhark: revista de investigación y cultura, No.9, 2014, hlm 467-481.
[7] Torres, Anna Elena. 2019. “The Anarchist Sage/Der Goen Anarkhist: Rabbi Yankev-Meir Zalkind and Religious Genealogies of Anarchism.” Diakses dari ingeveb.org.
[8] Penulis yang mengklaim bahwa Eduard Douwes Dekker adalah anarkis misalnya, teoretikus Marxis Belanda Frank van der Goes (1896), Nicolas Walter (2011), juga dua sejarawan Rusia Vadim Damier dan Kirill Limanov (2017).
[9] Multatuli. 1982. Max Havelaar, or, The coffee auctions of the Dutch Trading Company. Hlm 354-355.
[10] Multatuli. 1982. Ibid. Hlm 385.
[11] Frank van der Goes. Multatuli over Socialisme (1896).
[12] Kornelis ter Laan. Multatuli Encyclopedie (1995). Hlm 388.
[13] Surat Sikko Ernest Willem Roorda van Eysinga kepada Multatuli tertanggal 21 Agustus 1886. Diakses dari https://multatuli.online/brieven/datum/brief?j=1886&b=mdb07725
[14] Kornelis ter Laan. Multatuli Encyclopedie (1995). Hlm 21.
[15] Multatuli. 1982. Max Havelaar, or, The coffee auctions of the Dutch Trading Company. Hlm 368-369.
[16] Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Van Christen tot Anarchist (1910). Hlm 137.
[17] Surat Multatuli kepada John F. Snelleman tertanggal 30 Agustus 1886. Diakses dari https://multatuli.online/brieven/datum/brief?j=1886&b=mdb07735
